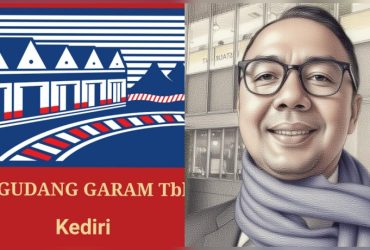WartaNiaga.ID – Sejarah dan Perkembangan Budidaya Tembakau di Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Era Modern, oleh Muhammad Kamil Sadili dan Mahendra Utama.
Sejarah dan Perkembangan Budidaya Tembakau di Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Era Modern
Oleh: Muhammad Kamil Sadili* dan Mahendra Utama**
1. Awal Masuk dan Penyebaran Tembakau di Nusantara
Tembakau pertama kali dikenal di Nusantara pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tanaman tembakau mulai dikenal masyarakat Jawa pada masa akhir pemerintahan Penembahan Senopati di Kerajaan Mataram, sekitar tahun 1601-1602 Masehi.
Berdasarkan naskah Babad Ing Sangkala, disebutkan dalam sebuah bait bahwa “Waktu mendiang penembahan meninggal di Gedung Kuning adalah bersamaan dengan mulai munculnya tembakau, setelah itu mulailah orang merokok”.
Tembakau diperkirakan dibawa ke Indonesia oleh bangsa Portugis yang menjajah Indonesia lebih dari satu abad (1512-1641), meskipun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa bangsa Spanyol yang membawanya setelah kedatangan mereka pada tahun 1521-1529.
Thomas Stamford Raffles dalam bukunya “The History of Java” (1817) mencatat bahwa sekitar tahun 1600-an tembakau telah banyak tumbuh di berbagai tempat di Jawa.
2. Masa Kolonial dan Sistem Tanam Paksa
2.1. Penerapan Cultuurstelsel untuk Tembakau
Pengembangan tembakau untuk pasar Eropa dimulai secara sistematis pada tahun 1830 melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch.
Sistem ini mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditas ekspor, termasuk tembakau, yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial.
Tembakau menjadi salah satu komoditas penting dalam sistem tanam paksa bersama dengan kopi, tebu, indigo, dan teh. Tanaman ini dikembangkan khususnya di daerah Rembang, Surabaya, Madiun, Kediri, Blitar, dan Priangan.
Sistem tanam paksa memberikan keuntungan besar bagi Belanda tetapi mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja dengan kondisi yang sangat buruk.
2.2. Dampak Sosial-Ekonomi Tanam Paksa
Pelaksanaan sistem tanam paksa tembakau menimbulkan berbagai dampak sosial-ekonomi yang signifikan:
a. Eksploitasi Tenaga Kerja: Petani dipaksa bekerja melebihi ketentuan awal yang seharusnya hanya 3 bulan setahun. Di daerah Parahyangan, laki-laki dari beberapa desa di distrik Simpur dipaksa bekerja di perkebunan indigo selama 7 bulan terus-menerus.
b. Kelaparan dan Kemiskinan: Akibat fokus pada tanaman ekspor, banyak petani tidak memiliki waktu untuk menggarap sawah dan tanahnya sendiri. Hal ini mengakibatkan kelaparan di berbagai daerah seperti Cirebon, Purwodadi, Demak, dan Grobogan.
c. Kritik dan Penghapusan: Sistem tanam paksa menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari kaum humanis Belanda seperti Eduard Douwes Dekker (Multatuli) yang mengangkat penderitaan rakyat melalui buku “Max Havelaar”. Sistem ini akhirnya dihapus secara bertahap antara tahun 1860-1870.
3. Perkembangan Perkebunan Tembakau Besar
3.1. Pusat-Pusat Produksi Tembakau Cerutu
Pada periode 1870-1940, pusat pengembangan tembakau cerutu di Indonesia berada di tiga wilayah utama yang memiliki kondisi agroklimatologi ideal:
– Deli (Sumatera Utara): Dikenal dengan tembakau cerutu kelas dunia untuk pembungkus (wrapper).
– Klaten (Jawa Tengah): Menghasilkan tembakau cerutu berkualitas tinggi.
– Karesidenan Besuki (Jawa Timur): Terkenal dengan tembakau Besuki Na-Oogst untuk isi cerutu.
3.2. Pendirian Perusahaan Perkebunan Besar
Usaha perkebunan tembakau secara besar-besaran dengan tujuan ekspor dimulai pada tahun 1856 oleh George Birnie, yang bekerja sama dengan Mr. C. Shanderberg Mattiessen dan A.D. Van Gennep. Mereka mendirikan perkebunan dengan nama “Landbouw Maatschappij Oud Djember (LMOD)”.
Beberapa tahun kemudian berdiri perusahaan perkebunan baru lainnya, antara lain:
– Landbouw Maatschappij Sukowono (LMS).
– Besoekische Tabaks Maatschappij (BTM).
– Amsterdam Besoekische Tabaks Maatschappij (ABTM).
Keberhasilan pemasaran tembakau Besuki ke pasar internasional menarik minat banyak pengusaha Belanda lainnya untuk berinvestasi di sektor perkebunan tembakau di Indonesia.
4. Era Pasca Kemerdekaan dan Nasionalisasi
4.1 Masa Transisi dan Bimbingan Petani
Pada tahun 1950, para pengusaha Belanda mendirikan Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia (YAPERRIN) yang bertujuan memberikan bimbingan teknis dan bantuan modal kepada petani tembakau. Namun, yayasan ini hanya bertahan hingga tahun 1957 karena perubahan politik dan kebijakan nasionalisasi.
4.2. Nasionalisasi Perusahaan Belanda
Dengan terbitnya Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, seluruh perusahaan perkebunan Belanda diambil alih menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menguasai sumber daya ekonomi strategis pasca kemerdekaan.
5. Restrukturisasi dan Pengembangan Modern
5.1 Transformasi Kelembagaan Perkebunan Tembakau
Tahun 1963, Kesatuan Jatim IX Tembakau dipecah menjadi PPN V Tembakau Besuki dan PPN VI Tembakau Besuki. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 (Lembaran Negara No. 23/1968), kedua perusahaan tersebut digabung kembali menjadi PT Perkebunan XXVII yang berkedudukan di Jember, dengan total 14 kebun.
Restrukturisasi kembali dilakukan pada tahun 1996. Berdasarkan PP No. 15 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, PTP XIX, PTP XXI-XXII, dan PTP XXVII dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X).
5.2. Restrukturisasi Terkini dan Merger
Seiring perkembangan, pada tahun 2023 pemerintah melalui PTPN Holding Perkebunan Nusantara melakukan restrukturisasi besar dengan menggabungkan beberapa anak perusahaan dalam bentuk klaster atau regionalisasi.
Pada 1 Desember 2023, PTPN X resmi dimerger dengan PTPN IX, dan keduanya dilebur menjadi PTPN I Regional 4 Unit Tembakau. Reorganisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, dan menekan biaya produksi yang tinggi.
Kemudian, pada 1 Juni 2024, PTPN I Regional 4 dan PTPN I Regional 5 kembali dilebur menjadi satu kesatuan dengan nama PTPN I Regional 5.
6. Kondisi Budidaya Tembakau Saat Ini
6.1 Unit Tembakau PTPN I Regional 5
Saat ini, Unit Tembakau PTPN I Regional 5 mengelola tiga kebun utama:
a. Kebun Ajong Gayasan (Kabupaten Jember, Jawa Timur).
b. Kebun Kertosari (Kabupaten Jember, Jawa Timur).
c. Kebun Klaten (Kabupaten Klaten, Jawa Tengah).
Hasil budidaya di Kebun Ajong Gayasan dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Pada tahun 2021, kebun ini memproduksi 5.983 ton daun hijau dengan rendemen 9,81% dan kualitas NW mencapai 27,10%.
6.2. Teknologi Budidaya dan Pengolahan
Proses budidaya tembakau di perkebunan modern melibatkan teknologi dan manajemen yang canggih:
A. Pembibitan: Menggunakan media tanam polybag sosis berukuran 4-5 cm dengan kapasitas 8000 bibit per bedengan. Seleksi bibit dilakukan dua tahap pada 10 dan 20 hari setelah sebar.
B. Pemeliharaan: Kriteria siap petik ditandai dengan pinggiran daun terdapat semburat kuning, muncul bunga sebanyak 5-10% per ha, dan angka klorofilmeter 290-320.
C. Pemanenan: Melibatkan tim khusus terdiri dari tenaga petik, tukang pikul, tukang sujen, tim rakit, dan tim menaikkan.
D. Pengolahan: Proses pengeringan daun dilakukan selama 18-20 hari tergantung material daun (daun kos, kak, dan teng) di gudang pengering yang dapat menampung 600.000 daun.
6.3. Dampak Perubahan Iklim
Fenomena kemarau basah belakangan ini berdampak signifikan terhadap budidaya tanaman tembakau di Jawa Timur. Masa tanam tembakau mundur karena hujan masih mengguyur dan banyak tanaman tembakau yang telanjur ditanam mati di usia muda.
Anomali cuaca ini juga mengancam kualitas produksi tembakau rajangan karena mayoritas petani mengandalkan panas matahari untuk mengeringkan daun tembakau dan membantu proses pewarnaan.
Petani di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, melaporkan bahwa masa tanam tahun 2025 mundur hampir sebulan bahkan sampai 1,5 bulan dibandingkan tahun sebelumnya karena masih ada hujan dengan intensitas tinggi.
7. Pasar Ekspor dan Kontribusi Ekonomi
7.1. Pencapaian Pasar Internasional
Tembakau Indonesia, khususnya dari Kebun Ajong Gayasan, berhasil menembus pasar ekspor ke BSB Group (Burger Soehne AG Burg) yang merupakan salah satu produsen cerutu internasional dari Swiss.
Tembakau ekspor harus memenuhi beberapa kriteria ketat untuk mendapatkan standar top grade, yaitu mutu daun NW (Natural Wrapper) dan LPW (Light Painted Wrapper) dengan indikator daun bersih, tidak sobek atau utuh, warna rata, dan ukuran daun < 38 cm dengan harga mencapai Rp 1 juta/kg.
7.2. Kontribusi dalam Produksi Nasional
Berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024, terdapat tiga sentra produksi tembakau utama di Indonesia berdasarkan rata-rata produksi tahun 2019-2023:
1. Jawa Timur: Produksi 117.930 ton/tahun (47,67% produksi nasional).
2. Nusa Tenggara Barat (NTB): Produksi 58.560 ton/tahun (23,67% produksi nasional).
3. Jawa Tengah: Produksi 53.500 ton/tahun (21,63% produksi nasional).
Di Jawa Timur sendiri, terdapat enam jenis tembakau yang dibudidayakan, yakni Besuki, Kasturi, Paiton, Madura, Virginia, dan tembakau Jawa.
Dari enam jenis tembakau itu, yang terbanyak atau 30% adalah tembakau Jawa, 18% Kasturi, 16% Madura, 12% Virginia, 11% Besuki, dan 10% tembakau Paiton.
8. Perkembangan Teknik Budidaya Inovatif
8.1. Sistem Tumpangsari dan Diversifikasi
Dalam upaya meningkatkan efisiensi lahan dan pendapatan petani, dikembangkan sistem tumpangsari (intercropping) antara tembakau dengan tanaman lainnya.
Penelitian di Timboa, Ngadirojo Village, Semarang Regency menunjukkan bahwa petani merespons positif introduksi budidaya gandum dengan sistem tumpangsari gandum dengan tembakau.
Melalui penyuluhan dan pelatihan praktis, petani menjadi mengetahui teknik budidaya gandum, produk olahan gandum, dan pemasarannya. Respons masyarakat menunjukkan keinginan untuk membudidayakan gandum sebagai alternatif tanaman yang dapat meningkatkan pendapatan.
8.2. Adaptasi Perubahan Iklim
Untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap budidaya tembakau, dikembangkan berbagai strategi adaptasi:
a. Penyesuaian Waktu Tanam: Mengubah jadwal tanam sesuai dengan pola hujan yang semakin tidak terprediksi.
b. Teknologi Pengeringan Alternatif: Pengembangan metode pengeringan yang tidak sepenuhnya bergantung pada sinar matahari.
c. Pemuliaan Varietas Tahan: Pengembangan varietas tembakau yang lebih tahan terhadap kondisi kelembaban tinggi
9. Peran Strategis dalam Perekonomian Nasional
Budidaya tembakau memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, khususnya dalam hal:
a. Penyerapan Tenaga Kerja: Menyediakan lapangan kerja bagi jutaan petani dan pekerja industri pengolahan tembakau.
b. Penerimaan Negara: Memberikan kontribusi signifikan melalui pajak dan devisa hasil ekspor.
c. Pengembangan Wilayah: Mendorong perkembangan daerah-daerah sentra produksi tembakau.
d. Nilai Budaya: Menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat di berbagai daerah sentra tembakau.
10. Tantangan dan Prospek Masa Depan
10.1. Tantangan Utama
a. Tekanan Kesehatan Global: Kampanye anti-tembakau yang semakin menguat secara internasional.
b. Perubahan Iklim: Anomali cuaca yang mengganggu proses produksi dan kualitas tembakau.
c. Regulasi Pemerintah: Kebijakan yang semakin ketat terkait produk tembakau.
d. Perubahan Preferensi Konsumen: Tren kesehatan yang mengurangi konsumsi produk tembakau.
10.2. Prospek Pengembangan
a. Diversifikasi Produk: Pengembangan produk tembakau non-rokok seperti ekstrak nikotin untuk farmasi.
b. Peningkatan Kualitas: Fokus pada produksi tembakau berkualitas tinggi untuk pasar premium.
c. Agrowisata Tembakau: Pengembangan wisata perkebunan tembakau seperti yang telah dilakukan di Klaten.
d. Ekspansi Pasar Ekspor: Peningkatan nilai ekspor melalui produk tembakau berkualitas tinggi.
11. Kesimpulan
Budidaya tembakau di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan transformasi signifikan sejak pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-17.
Dari sekadar tanaman baru yang diperkenalkan oleh bangsa Portugis dan Spanyol, tembakau berkembang menjadi komoditas perkebunan penting yang memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia.
Perkembangan budidaya tembakau tidak terlepas dari pengaruh kebijakan kolonial Belanda melalui sistem tanam paksa, yang meninggalkan warisan infrastruktur dan pengetahuan budidaya meskipun dengan konsekuensi kemanusiaan yang berat.
Pasca kemerdekaan, transformasi kelembagaan melalui nasionalisasi dan restrukturisasi membawa pengelolaan perkebunan tembakau ke dalam era baru di bawah pengelolaan BUMN.
Ke depan, budidaya tembakau di Indonesia menghadapi tantangan kompleks terkait isu kesehatan, perubahan iklim, dan regulasi. Namun, dengan strategi yang tepat yang berfokus pada kualitas, nilai tambah, dan diversifikasi, budidaya tembakau masih dapat memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian nasional, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan menghasilkan devisa melalui ekspor produk tembakau berkualitas tinggi. (*)
———————————————————————-
Tentang Penulis:
*Muhammad Kamil Sadili, adalah seorang pelajar, peneliti tani, ternak, pedagang, serta ayah dari anak-anak yatim dan dhuafa di Persada Yatim Indonesia (PYI), sebuah organisasi media belajar dan berbagi.
**Mahendra Utama, adalah Eksponen Aktivis 98. Saat ini ia menduduki beberapa posisi strategis, antara lain Komisaris Utama PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis, di Sumatera Utara, Komisaris PT Mitratani Dua Tujuh, di Jember.